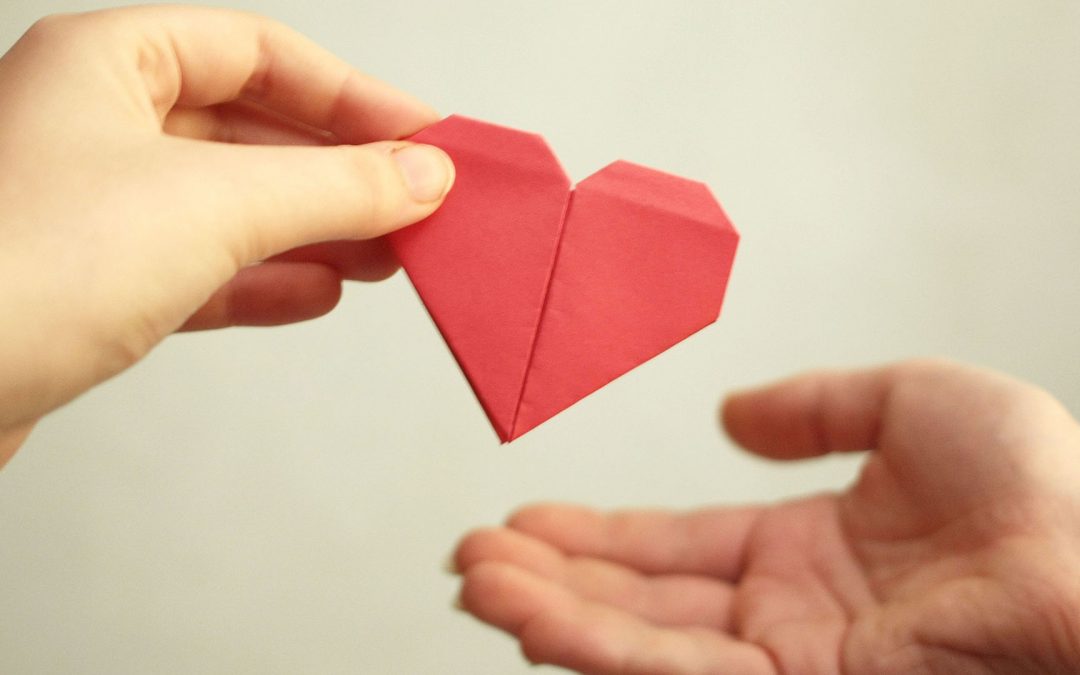Kisah Curahan Hati Seorang Bapak di Pesawat
Kadang kita bertanya, mana yang harus didahulukan. Misalnya, mendidik anak menjadi saleh atau pintar? Kisah berikut ini layak jadi pertimbangan. Kisah ini Aa kutip dari sebuah tulisan inspirasi.
Seorang bapak kira-kira usia 65 tahun duduk sendiri di sebuah lounge Bandara Halim Perdana Kusuma, menunggu pesawat yang akan menerbangkannya ke Yogya. Kami bersebelahan hanya berjarak satu kursi kosong. Beberapa menit kemudian ia menyapa saya.
“Dik hendak ke Yogya juga?”
“Saya ke Blitar via Malang, Pak. Bapak ke Yogya?”
“Iya.”
“Bapak sendiri?”
“Iya.” Senyumnya datar. Menghela napas panjang. “Dik kerja di mana?”
“Saya serabutan, Pak,” sahut saya sekenanya.
“Serabutan tapi mapan, ya?” Ia tersenyum. “Kalau saya mapan tapi jiwanya serabutan.”
Saya tertegun. “Kok begitu, Pak?”
Ia pun mengisahkan, istrinya telah meninggal setahun lalu. Dia memiliki dua orang anak yang sudah besar-besar. Yang sulung sudah mapan bekerja di Amsterdam pada sebuah perusahaan farmasi terkemuka dunia. Yang bungsu, masih kuliah S2 di Amerika Serikat.
Lalu ia berkisah tentang rumahnya yang mentereng di kawasan elit Pondok Indah Jakarta. Rumah itu hanya dihuni olehnya seorang, ditemani seorang satpam, dua orang pembantu dan seorang supir pribadinya. Ia menyeka airmata.
“Dik jangan sampai mengalami hidup seperti saya ya. Semua yang saya kejar dari masa muda, kini hanyalah kesia-siaan. Tiada guna sama sekali dalam keadaan seperti ini. Saya tak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi saya sadar, semua ini akibat kesalahan saya yang selalu memburu duit, duit, dan duit. Sampai lalai mendidik anak tentang agama, ibadah, silaturahim, dan berbakti pada orangtua.
Hal yang paling menyesakkan dada saya ialah saat istri menjelang meninggal dunia karena sakit kanker rahim yang dideritanya. Anak kami yang sulung hanya berkirim SMS tak bisa pulang mendampingi akhir hayat mamanya gara-gara harus meeting dengan koleganya dari Swedia. Sibuk. Iya, sibuk sekali. Sementara anak bungsu saya mengabari via WA bahwa ia sedang mid-test di kampusnya sehingga tidak bisa pulang.”
“Bapak, yang sabar ya.” Tidak ada kalimat lain yang bisa saya ucapkan selain itu.
Ia tersenyum kecut, “Sabar sudah saya jadikan lautan terdalam dan terluas untuk membuang segala sesal saya Dik. Meski telat, saya telah menginsafi satu hal yang paling berharga dalam hidup manusia, yakni sangkan paraning dumadi. Bukan materi sebanyak apa pun. Tetapi, dari mana dan hendak ke mana kita akhirnya. Saya yakin, hanya dari Allah dan kepada-Nya kita kembali. Di luar itu, semua semu. Tidak hakiki. Adik bisa menjadikan saya contoh kegagalan hidup manusia yang merana di masa tuanya.”
Ia mengelus bahu saya, dan saya tiba-tiba teringat sosok ayah. Spontan saya memeluk bapak tersebut. Tak sadar menetes airmata. Bapak tua tersebut juga meneteskan airmata. Kejadian ini telah menyadarkan saya bahwa mendidik anak tujuan utamanya harus saleh bukan kaya. Tanpa kita didik pun rezeki anak sudah dijamin oleh Tuhan. Tapi tidak ada jaminan tentang keimanannya. Orangtua yang harus berusaha untuk mendidik dan menanamkannya.
Di pesawat seusai take off, saya melempar pandangan ke luar jendela. Ke kabut-kabut yang berserak bergulung-gulung. Terasa diri begitu kecil lemah tak berdaya di hadapan kekuasaan-Nya. Hidup itu sederhana saja. Carilah rezeki. Jangan mengejar jumlahnya, tapi kejar berkahnya. (KH. Abdullah Gymnastiar)