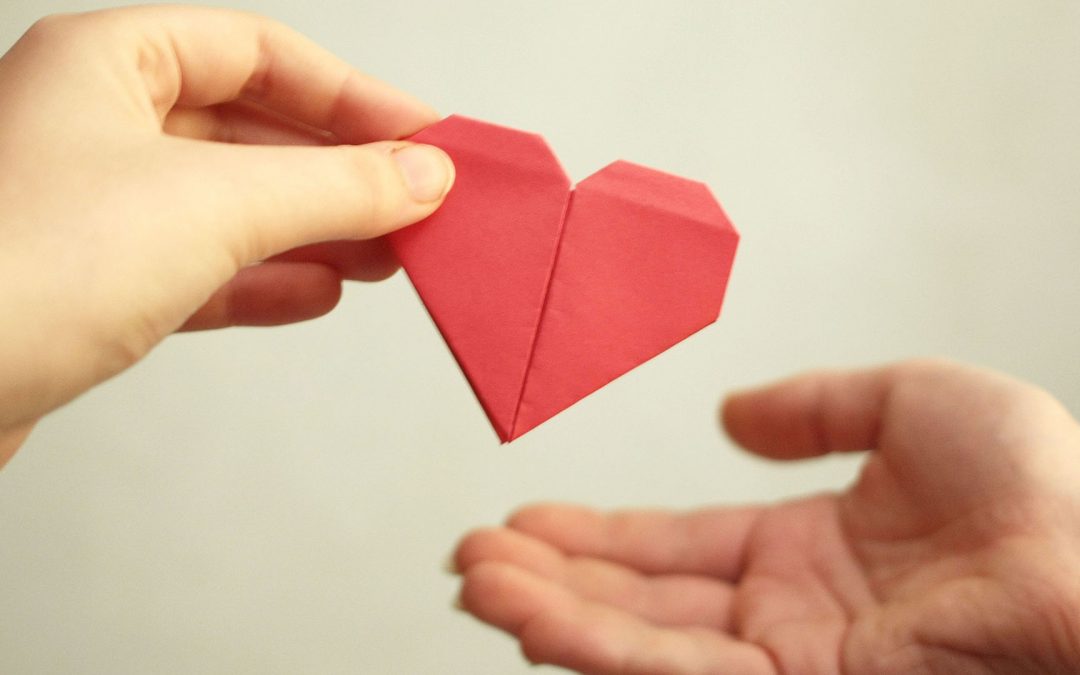Berburu “Keterikatan” hingga ke Daarut Tauhiid Bandung
Sewaktu Aa Gym masih berjaya dengan popularitasnya, saya malah nggak pernah tertarik untuk “meninjau” ke pondok pesantren yang beliau pimpin, Daarut Tauhiid di Kota Bandung. Kunjungan pertama saya justru terjadi secara spontan baru-baru ini. Saat tiba-tiba terpikir untuk menepi sejenak dari rutinitas melelahkan yang terbiasa saya jalani sehari-hari. Begitu membuka websitenya dan menemukan bahwa mereka punya program santri mondok jangka pendek (1 bulan) untuk dewasa-umum (Dauroh Qolbiyah), saya langsung tertarik untuk mendaftar.
Tanggal 10 September lalu, secara dadakan saya putuskan mendatangi alamat pondok pesantren itu dari Jakarta. Dan saat masuk ke kawasan Jalan Gegerkalong Girang, saya langsung jatuh hati. Kawasan pesantren ini ternyata bukan seperti yang saya bayangkan sebelumnya (kirain berupa kompleks khusus dengan gerbang tinggi dan eksklusif di mana para santri prianya berseliweran dengan menggunakan sarung dan peci hitam, hehe.. norak deh saya). Ternyata tempat ini hanya sebuah kawasan seperti lingkungan pemukiman biasa secara fisik, tapi suasananya itu langsung berhasil membuat saya merasa adem dan nyaman. Mengesankan aura religius, ramah, bersahaja, bermartabat, santun, dan cerdas.
Dulu waktu masih kecil dan remaja, saya sering bertanya-tanya dalam hati: gimana ya rasanya kalo kita menjadi santri mondok di sebuah pesantren? Tinggal di lingkungan “tertutup” yang semuanya serba diatur dengan jadwal ketat, dijaga dengan berbagai rambu pergaulan yang (sebagai anak kecil saat itu) mungkin saya sendiri bahkan nggak ngerti maknanya apa. “Dipaksa” untuk mempelajari berbagai ilmu agama “tingkat tinggi” yang terkadang malah seperti terlalu abstrak kalau disandingkan dengan kondisi kehidupan riil sehari-hari. Harus ini, harus itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Kalo saya sih bisa mati gaya sambil berdiri kali ya.
Tapi semasa kuliah, saya malah justru pernah punya teman dekat cowok yang alumnus sebuah pondok pesantren paling besar di Jawa Timur. Setamat SMA, sebelum akhirnya meneruskan kuliah lagi di kampus yang sama dengan saya di Bogor, beliau sempat mondok dulu selama 4 tahun. Dan dari beliaulah jadinya saya sering mendengar banyak cerita seru tentang kehidupan sehari-hari para santri laki-laki di ponpes itu. Yang kalau menurut saya sih, jauh dari bisa dibilang asik.
Sebenarnya sampai beberapa bulan lalu pun pendapat saya tentang kehidupan di pondok pesantren juga masih sama dengan waktu kecil dulu: bukan saya banget. Karena sepertinya kok (ini hanya opini saya sebagai “orang luar” loh…) penuh “pemaksaan” perihal doktrin-doktrin agama. Di mata saya, kesannya kita seolah-olah dituntut untuk hidup “tanpa alternatif”. Ikutin aja semua aturan yang berlaku. Semua pemikiran harus “seragam” mengikuti pola yang tertulis di “buku panduan”. Seakan-akan kita bisa menjadi manusia mulia cukup kalau sudah dibekali ilmu agama, meskipun kadang tanpa dibarengi pemahaman spiritual yang bening dan mumpuni.
(Karena belajar menjadi spiritual (kalo menurut saya) berarti membebaskan seseorang untuk berpikir sesukanya dulu aja. Dibimbing memang harus, tapi dibebaskan juga wajib. Sampai suatu ketika seseorang itu bisa menemukan ilham tentang “rumah sejati” yang membuat dia merasa nyaman lahir batin, lalu stay, dan kemudian silakan aja mau memilih aturan (agama) mana yang ia sukai. Misalnya kalo bagi saya Islam yang paling nyaman, yaa… saya akan menjadi seorang muslimah yang menjalankan aturan agama dengan kesungguhan, karena inti kesadaran spiritualnya sudah saya dapatkan. Agama adalah “raga” sedangkan spiritual adalah “jiwa”.
Padahal agama cuma aturan-aturan dasar aja, kan ya? Semacam kumpulan pasal-pasal yang harus diterapkan untuk kebaikan bersama di dunia. Sementara ruh dari sekumpulan aturan dasar itu adalah spiritualitas masing-masing individu. Agama bisa menjadi kebaikan yang nyata hanya kalau ditegakkan oleh orang-orang yang punya kesadaran spiritual. Sebaliknya juga bisa mati atau sekadar jadi bayang-bayang semu ketika digenggam oleh sekelompok orang yang belum/tidak punya ruh spiritual memadai).
Belum lagi soal gaya hidup para santri di pondok pesantren yang (konon, katanya) selalu serba kolektif. Kalo buat saya pasti nggak cocok, karena sudah terlanjur terbiasa diizinkan punya privacy sejak kecil. Yang nggak bisa ditembus sembarang orang kecuali kalo saya persilakan sebelumnya.
Dan lain-lain imej “negatif” di kepala saya perihal pondok pesantren yang sudah terlanjur mengendap di otak (padahal pastinya belum tentu benar dong isi otak saya itu). Yang jelas, judulnya kalau pun dulu sampai dipaksa-paksa, tetap nggak mungkinlah saya bersedia dengan sukarela masuk pondok pesantren (meskipun keinginan untuk “merapat” melalui jalur agama sangat kuat, tapi gaya pengajarannya itu loh… khawatirnya yang ada malah bisa-bisa bikin stres dan ujung-ujungnya berakibat kapok belajar agama lagi, saking antinya saya diatur-atur dan dipaksa-paksa).
Sampai sejak beberapa bulan belakangan ini, pendapat saya mulai bergeser secara lumayan jungkir balik. Mungkin karena rindu pada sesuatu yang bisa membuat hati merasa damai secara permanen, ditambah juga kelelahan menghadapi berbagai “perang batin” dalam keseharian, sekarang saya sedang berpikir untuk “melepaskan” semua kehidupan duniawi dan sejenak “bersembunyi” untuk belajar memahami segala sesuatu dari kacamata agama. Belajar menerima apa pun “tanpa syarat”. Serta mulai secara khusus berusaha mendekat pada Sang Maha Pencipta (yang selama ini karena alasan sok sibuk kurang sekali saya lakukan). Dan kalau itu artinya saya harus bersedia mondok dan “terikat” dengan berbagai aturan ala pesantren (karena kalau kita mondok, berarti kita harus bersedia “diatur” selama 24 jam dalam sehari), kali ini saya malah bersedia dengan sukarela. Bahkan plus bersemangat.
Semoga aja berawal dari sebuah sudut yang nyaman di Kota Badung ini, satu persatu banyak hal bisa segera saya temukan sebagai “jawaban” atas berbagai pertanyaan (asal bukan termasuk “jawaban” berupa pertemuan kembali dengan “pria ajaib” yang tiba-tiba ngajakin “seriusan”, padahal baru kenalan setengah jam di sebuah warung di jalan Gegerkalong Girang ini.. hahahaha… geloo). (Riri)
sumber: kompasiana.com/riri.s